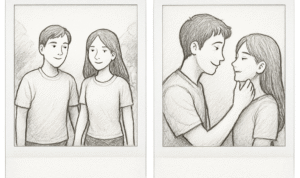Dari balik warung sederhananya yang berdinding papan dan beralaskan terpal, Mbok Yem menyajikan nasi pecel, mie instan, gorengan, hingga kopi panas. Namun lebih dari itu, ia menyajikan kehangatan manusiawi yang begitu langka ditemukan di alam bebas.
Perempuan Tangguh Tanpa Pamrih
Mbok Yem dikenal tak pernah mematok harga mahal. Di ketinggian yang menantang logistik, ia tetap menjual makanan dengan harga murah. Ia tahu, sebagian besar pendaki adalah mahasiswa atau pekerja muda dengan anggaran terbatas. “Yang penting mereka bisa makan, bisa kuat sampai bawah,” begitu kata-katanya yang kerap dikenang para pendaki.
BACA JUGA: Resep Ayam Bakar Enak dan Empuk, Cita Rasa Nusantara yang Tak Pernah Gagal Menggoda Selera
Tidak sedikit pula pendaki yang dibantunya secara sukarela. Dari yang kedinginan, tersesat, bahkan sakit, Mbok Yem tak segan turun tangan. Ia menolak disebut pahlawan. Ia hanya ingin semua orang selamat dan pulang.
Tradisi Turun Gunung Menjelang Lebaran
Setiap tahun, menjelang Lebaran, Mbok Yem akan turun gunung. Bukan untuk liburan, tapi untuk berkumpul dengan keluarga dan menjalankan ibadah Idul Fitri. Tradisi ini menjadi penanda bahwa warung di puncak akan “libur sementara”.
Namun tahun ini berbeda. Sejak awal 2025, kesehatannya terus menurun. Ia mengidap pneumonia dan harus turun lebih awal. Dalam kondisi lemah, ia ditandu oleh enam orang dari puncak menuju desa.
Warisan yang Tak Akan Hilang
Kini, kepergian Mbok Yem meninggalkan kekosongan tak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Warungnya masih ada, namun sosok hangat di balik dapur kecil itu telah tiada. Ribuan pendaki yang pernah singgah, kini hanya bisa mengenang aroma nasi pecel dan suara khas “monggo mlebet nduk, le.”